Surat edaran itu ditandatangani 24 April 2025. Instruksinya jelas dan rinci: Seluruh insan pendidikan diharapkan mengenakan pakaian adat daerah saat upacara bendera Hardiknas 2 Mei esok hari. Logo sudah dirilis, tema sudah ditetapkan: "Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua."
Warna-warni kebhinekaan akan jelas menghiasi setiap halaman sekolah. Merah, biru, abu-abu, dan bintang emas dalam logo akan menjelma menjadi batik, ulos, kebaya, baju bodo, dan beragam busana tradisional dari Sabang hingga Merauke. Sangat indah dan menggugah rasa nasionalisme, tentu saja. Siapa yang akan bisa menolak keindahan visual ini?
Tapi di tengah seremonial berwarna-warni itu, izinkan saya bertanya: Apakah makna "partisipasi semesta" dan "pendidikan bermutu untuk semua" telah benar-benar kita renungkan? Atau sekadar jargon tahunan yang berganti bersama logo dan warna tema?
Partisipasi Semesta dalam Pakaian, Absen dalam Infrastruktur
Sementara kita sibuk memilih pakaian adat terbaik untuk upacara Hardiknas, ada fakta menohok yang hampir luput dari perhatian publik. Kepala Biro Perencanaan Kemendikdasmen Vivi Andriani mengungkapkan pada rapat dengar pendapat dengan Panja Pendidikan Komisi X DPR (4/3/2025): "Dari total satuan pendidikan di daerah 3T sebanyak 20 ribu, 10 ribunya masih dalam kondisi rusak."
Bayangkan saja. Setengah dari seluruh sekolah di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal kita sedang sekarat secara fisik. Rusak sedang hingga berat. Tanpa perpustakaan, kekurangan ruang kelas, tanpa listrik, tanpa internet. Jika diurai, ada 12.064 sekolah tanpa perpustakaan, 4.988 sekolah kekurangan ruang kelas, 5.783 sekolah tanpa listrik, dan 10.692 sekolah tanpa akses internet.
Angka-angka ini bukan sekadar statistik semata. Ini adalah potret nyata masih timpangnya sistem pendidikan kita. Di satu sisi, kita berapi-api bicara "partisipasi semesta" dan "pendidikan bermutu untuk semua." Di sisi lain, kita membiarkan separuh anak bangsa di daerah 3T belajar di bawah atap bocor, duduk berdesakan, tanpa buku bacaan, tanpa daya listrik untuk menyalakan lampu, tanpa internet untuk mengakses dunia.
Ada ironi halus dalam instruksi mengenakan pakaian adat pada peringatan Hardiknas 2025 ini. Di satu sisi, kita merayakan keberagaman budaya Indonesia melalui busana tradisional. Di sisi lain, sistem pendidikan kita masih sangat tersentralisasi dan seragam, bahkan dalam kerusakannya. "Kerusakan (yang) merata" dari Sabang sampai Merauke, tapi penyelesaiannya tidak kunjung datang.
Kemiripan Menyedihkan: Sekolah Rakyat dan Sekolah Roboh
Entah kebetulan atau hanya ironi takdir semata, hampir bersamaan dengan tersebarnya surat edaran Hardiknas, pemerintah dengan bangga meluncurkan Program Sekolah Rakyat (SR). Digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan dikelola oleh Kementerian Sosial, SR menjanjikan pendidikan gratis, fasilitas lengkap, sistem berasrama penuh, dan beasiswa untuk memutus rantai kemiskinan.
Sebuah gagasan yang mulia, tentu saja. Tapi secercah keraguan muncul: apakah kita butuh Sekolah Rakyat baru sementara 10 ribu sekolah yang sudah ada sedang sekarat? Bukankah lebih masuk akal memperbaiki yang rusak sebelum membangun yang baru?
Bintang Emas di Logo, Langit Bolong di Kenyataan
Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya belajar saat hujan turun? Bukan rasa nyaman yang dibayangkan kebanyakan orang. Bagi ribuan siswa di pelosok negeri, hujan berarti bencana kecil: tetesan air dari atap yang bocor, papan tulis yang basah, buku dan seragam yang lembab. Ketika petir menyambar, listrik padam. Pembelajaran terhenti.
Di pelosok Indonesia, realitas pendidikan jauh dari kilau bintang emas di logo Hardiknas. Tak ada gemerlap, yang ada hanya perjuangan sehari-hari. Guru-guru honorer dengan gaji di bawah UMR menempuh jarak puluhan kilometer untuk mengajar. Mereka bertahan bukan karena insentif yang memadai, tapi karena panggilan nurani yang tak bisa diabaikan begitu saja.
Ratusan sekolah di pulau-pulau kecil, di lereng gunung, dan di tengah hutan berdiri tegak berkat tekad baja masyarakat setempat. Tanpa menunggu uluran tangan pemerintah, warga bergotong royong membangun ruang belajar seadanya. Mereka menyulap bambu menjadi dinding, daun rumbia menjadi atap. Tak ada laboratorium canggih, tak ada perpustakaan digital. Yang ada hanya tekad untuk memastikan anak-anak mereka mendapat pendidikan, bagaimanapun caranya.

 3 months ago
22
3 months ago
22







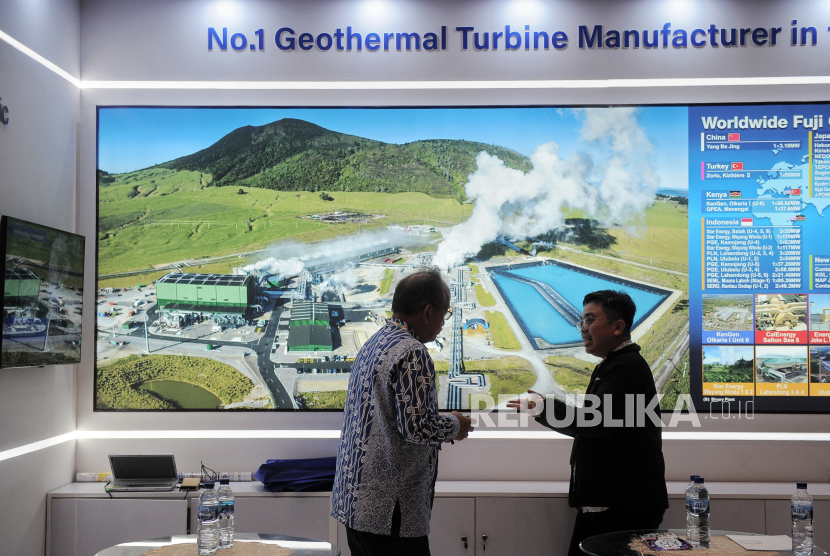






 English (US) ·
English (US) ·