Fenomena ini bukanlah sekadar gejala kantong kering, melainkan cermin retak yang memantulkan krisis multidimensi: kerapuhan ekonomi, pergeseran psikologis, dan disrupsi teknologi yang tak terhindarkan. Rojali dan Rohana bukanlah hantu yang harus diusir, melainkan utusan dari masa depan yang sedang menertawakan model bisnis yang sekarat.
Rojali adalah manifestasi dari kelas precariat. Istilah yang dipopulerkan oleh ekonom Guy Standing ini merujuk pada kelas sosial yang hidup dalam ketidakpastian, tanpa jaminan pendapatan atau stabilitas kerja.
Laporan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) dan temuan Mandiri Spending Index, mengindikasikan bahwa masyarakat mulai "menggerogoti tabungan", mengonfirmasi eksistensi kelas ini. Mereka mungkin memiliki daya beli, namun ketakutan akan masa depan membuat mereka sangat berhati-hati.
Mereka datang ke mal bukan karena tidak punya uang, tetapi karena mal menawarkan "kemewahan gratis": pendingin udara, hiburan visual, dan rasa aman sementara dari kerasnya realitas ekonomi. Mereka menahan belanja bukan karena miskin, tapi karena cemas. Ini bukan lagi soal daya beli, ini soal daya tahan.
Mal telah gagal memahami evolusi kebutuhan manusia. Teori "The Experience Economy" dari B. Joseph Pine II dan James H. Gilmore, yang ditulis lebih dari dua dekade lalu, kini menjadi relevansi absolut. Manusia tidak lagi membeli barang, mereka membeli pengalaman dan transformasi. Mal yang masih mendefinisikan diri sebagai "tempat menjual barang" sudah mati, hanya saja belum dikuburkan.
Faktanya sektor F&B (makanan dan minuman) di mal cenderung lebih stabil. Mengapa? Karena makan bersama adalah pengalaman sosial. Rojali dan Rohana datang ke mal untuk mencari pengalaman, bukan sekadar etalase produk. Ketika satu-satunya pengalaman yang ditawarkan adalah transaksi jual-beli, sementara kebutuhan primer mereka adalah koneksi dan rekreasi, maka yang terjadi adalah gesekan antara ekspektasi pengunjung dan proposisi nilai mal.
Mereka datang untuk "cuci mata", sebuah stimulasi visual yang gratis, karena mal gagal menawarkan pengalaman lain yang sepadan dengan uang yang harus mereka keluarkan.
Rohana adalah konsumen phygital (physical-digital) yang jauh lebih cerdas dari para peritel. Mereka adalah pelaku showrooming yang ulung. Mereka datang ke toko fisik untuk menyentuh, mencoba, dan merasakan produk, lalu memindai barcode atau mencari nama produk tersebut di ponsel mereka untuk membelinya dengan harga lebih murah di e-commerce.
Mereka tidak "jarang beli", mereka hanya tidak membeli di sana. Kegagalan peritel bukanlah karena Rohana, tetapi karena mereka gagal membangun jembatan yang mulus antara kanal fisik dan digital mereka. Mereka melihat pengunjung sebagai entitas fisik murni, padahal setiap pengunjung adalah portal menuju dunia digital yang tak terbatas di genggaman mereka.
Lalu, Apa Solusinya? Berdamai dengan Hantu!
Maka, alih-alih mengusir "hantu" ini, para pengelola...

 2 months ago
41
2 months ago
41



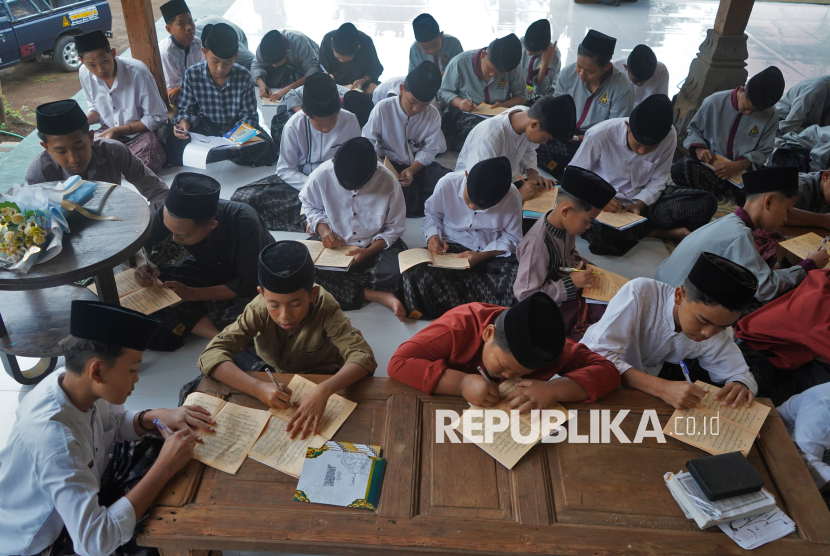










 English (US) ·
English (US) ·